Esai Epistoholica No. 89/Januari 2010
Email : humorliner (at) yahoo.com
Home : Epistoholik Indonesia
 Tahun Baru 2010 saya rayakan bersama Bach.
Tahun Baru 2010 saya rayakan bersama Bach. Bukan Bakhuri, Bachtiar atau Bachrudin. Juga bukan Bacharah. Tetapi Bach. Komponis Jerman. Johann Sebastian Bach (1685–1750).
“Ketika para malaikat melantunkan puja-puji kepada Tuhan barangkali mereka hanya memainkan karya-karya Bach. Tetapi bila mereka berkumpul bersama antarmereka sendiri dan keluarganya, saya yakin mereka akan memainkan Mozart,” tulis seorang teolog Protestan Swiss, Karl Barth (1886–1968) yang membandingkan Bach dengan Mozart.
Komparasi yang menarik. Walau saya tidak tahu apakah Tuhan akan menjadi murka atau tersinggung apabila Dia dipuji, misalnya dengan suguhan permainan “A Musikal Joke”-nya Mozart yang glenyengan bin selengekan itu ?
Yang saya tahu, merujuk karya-karya Bach itu seorang Sting, pentolan kelompok musik punk rock The Police yang sohor tahun 80-an, pernah berujar : “Kalau saya mendengarkan Bach, saya seperti sedang mendengarkan arsitektur.” Tangan Sting saat itu yang saya tonton di saluran National Geographic, nampak terentang ke atas.
Katedral.
Begitulah gambaran spontan yang segera muncul di kepala saya. Termasuk pula ketika pagi tanggal 1 Januari 2010 itu saya mendengarkan nomor “Jesu..Joy of Maria Dancing” yang salah satu karya Bach tersebut.
Manusia setengah dewa. Pagi itu, nampaknya saya diusik agar mendengarkan Bach secara naluriah. Mungkin sebagai cerminan dorongan kata hati, bawah sadar, untuk mau mendengar suara-suara pujian bagi Illahi. Boleh jadi sebagai manifestasi ucapan bersyukur karena saya masih bisa menjejaki tahun 2010 ini.
Sebab pagi itu sebenarnya saya ingin sekali mendengarkan karya Ludwig van Beethoven (1770–1827). Utamanya nomor Simfoni No. 9 yang pernah dipopkan oleh penyanyi Spanyol di tahun 70-an, Miguel Rios.
Dengan judul “Song of Joy.”
Saya ingin mendengarnya, karena nomor itu merupakan nomor kesayangan Gus Dur. Guru bangsa, guru humoris dan bapak pluralisme itu baru saja wafat, Rabu, 30 Desember 2009.
Diwartakan pula, sebelum mencapai masa kritis pada tanggal 30 Desember 2009 petang, Gus Dur ingin mendengarkan buku audio. Sampai saat ini saya dan kita semua tidak tahu tentang judul-judul buku audio apa saja yang menemani beliau saat sakit hingga wafatnya itu.
 Terkait buku audio itu seorang warga Indonesia yang menempuh gelar doktor di Jerman, Poltak Partogi Nainggolan pernah menulis di koran Seputar Indonesia, 2-3 April 2008 yang lalu.
Terkait buku audio itu seorang warga Indonesia yang menempuh gelar doktor di Jerman, Poltak Partogi Nainggolan pernah menulis di koran Seputar Indonesia, 2-3 April 2008 yang lalu. Judul artikelnya, “Manusia Setengah Dewa.”
Untuk keperluan disertasinya di Universiteit Freiburg, Jerman, ia mewawancarai Gus Dur, yang kebetulan saat itu sedang sakit.
Dalam artikelnya itu ia bercerita, walau dalam keadaan sakit dan praktis tidak mampu lagi membaca, Gus Dur tetap mengasupi otaknya dengan sumber-sumber pengetahuan mutakhir melalui buku-buku audio itu. Kegetolan Gus Dur untuk terus belajar, barangkali sebagai penyebab mengapa seorang kerabatnya yang kini tinggal di Belanda, Musayin, di depan corong Radio Hilversum (1/1/2010) pagi, menjelaskan betapa jauhnya perbedaan visi antara Gus Dur dengan “seteru” sekaligus keponakannya sendiri, Muhaimin Iskandar.
“Antarkeduanya berbeda 20 tahun,” kata Musayin. Apalagi beliau dengan kita-kita yang rakyat biasa ini. Kelebihan Gus Dur tersebut barangkali pula justru membuat interaksinya dengan orang kebanyakan menjadi seperti yang digambarkan oleh John Naisbitt dalam bukunya Mind Set ! (2006).
Futuris itu telah mengutip visi kepemimpinan seorang Al Smith, gubernur New York yang pernah berkampanye untuk kursi presiden AS pada tahun 1928. Katanya, “Jangan terlalu jauh di depan parade sampai-sampai orang tidak tahu kalau kau termasuk di dalamnya.”
Gus Dur, pastinya, juga berada jauh di depan parade untuk urusan humor pula di Indonesia. Untuk berusaha ikut mendekatkan, saya pernah menulis usul-usil dalam bentuk surat pembaca berjudul “Komedian Islam Vs Ustadz Gaul” yang saya kirimkan ke Majalah Gatra, 25 Oktober 2005. Saya tidak tahu dimuat atau tidak. Isinya :
“Fenomena ustadz gaul seperti dilaporkan GATRA (29/10/2005) sungguh menarik. Mereka melakukan syiar agama Islam bermediakan kesenian, seperti nyanyian dan humor, mengingatkan kiprah Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, yang melakukan syiar Islam bermediakan wayang. Pendekatan budaya ini terbukti ampuh ketimbang pendekatan kekerasan atau penaklukan.
Di Amerika Serikat, syiar Islam kontemporer lebih radikal lagi. Bermediakan humor. Syiar Islam ini secara intensif dilakukan pasca serangan teroris 11 September 2001 yang menimbulkan ketegangan hebat antara Islam vs Barat, seperti disebut oleh Samuel Huntington sebagai benturan peradaban.
Oleh kalangan komedian muslim Amerika seperti Azhar Usman, Preacher Moss, Azeem, Ahmed Ahmed, Maysoon Zayid sampai Tissa Hami, benturan peradaban itu diwujudkan dalam perang bermediakan lawakan. Tidak untuk saling mengejek, melainkan untuk menumbuhkan saling pemahaman.
Tahun 2004, Azhar Usman, Preacher Moss dan Azeem menggagas tur pentas komedi keliling Amerika bertajuk Allah Made Me Funny Tour untuk memromosikan Islam sebagai agama cinta damai dan anti tindak kekerasan.
“Gagasan tur ini adalah menyediakan bagi kalangan muslim dan non-muslim wahana gaul dalam zona aman, relevan, inklusif, di mana humor dimanfaatkan untuk menjembatani jurang bias, sikap tidak toleran dan penyakit sosial lainnya”, kata Preacher Moss, penggagasnya.
Orang tidak suka dikhotbahi, kata Moss, sehingga lelucon dia anggap lebih efektif dalam memberikan edukasi bagi kalangan muslim atau pun non-muslim. Berbeda dibanding khotbah, lelucon mampu mengajak penonton berpikir, beperanserta dan melangsungkan dialog dengan para penampil.
Di fron lain ada pula aksi komedian Ahmed Ahmed, muslim Amerika kelahiran Mesir bersama Bob Alper, komedian dan juga seorang rabbi Yahudi, melakukan tur komedi berdua. Dengan tema “Satu Arab, Satu Yahudi, Satu Panggung” mereka menggotong misi untuk meredakan ketegangan dan prasangka hubungan antarbangsa melalui humor. Pentasnya di Denver dipenuhi penonton, baik dari kalangan Islam, Kristen dan juga Yahudi.
Bagaimana di Indonesia ? Kita kenal humoris muslim yang ulung seperti Gus Dur, Mustofa Bisri sampai Emha Ainun Nadjib. Sebagai pengelola situs blog berisi kajian seputar masalah komedi, saya ingin bertanya : setelah ustadz gaul, kapankah komunitas muslim kita mampu menghadirkan komedian muslim sekaliber Azhar Usman yang leluconnya cerdas, toleran, tidak ada pornonya sama sekali dan sekaligus tajam, di Indonesia ?”
Dahsyat di dunia maya. Gus Dur sebagai sosok “manusia setengah dewa” memang sulit bagi kita untuk menahannya untuk tidak berlari dalam parade penciptaan humor-humor cerdas sampai sebagai pionir proses demokratisasi di Indonesia. Status yang sama, tetapi dalam ranah yang tak terduga, nampak juga dikukuhkan sehari sesudah beliau meninggal dunia.
Radio BBC Siaran Indonesia, Kamis 31 Desember 2009, malam hari, mewartakan berita menarik. Diucapkan oleh penyiar BBC yang sering mengkaji masalah teknologi informasi, Muhammad Susilo, bahwa tercatat prestasi luar biasa untuk kata “gus dur” pada Twitter.com, situs jaringan sosial dan microblogging yang populer itu.
Menurutnya, kata “gus dur” hari itu meroket dan menempati peringkat ke-4 di antara jutaan istilah yang berseliweran, yang diposting oleh jutaan pemakai Twitter dari seluruh dunia. Bahkan para pemilik akun Twitter dari manca negara sampai-sampai bertanya-tanya tentang apa dan siapa “gus dur” tersebut.
Fakta itu menunjukkan, begitu Muhammad Susilo menyimpulkan, betapa nama Gus Dur juga memiliki kharisma yang dahsyat di dunia maya. Kebetulan, sebagai pemakai akun Twitter sejak 17 Juli 2009, saat itu saya juga telah memposkan 3 tweets, komentar saya terkait warisan luhur humoris dari Gus Dur bagi kita bangsa Indonesia dan dunia.
Bis-bis Beethoven. Terkait Gus Dur dan kota saya Wonogiri, secara guyon dapat dikatakan bila dirinya lebih mudah diingat bila dikaitkan dengan beberapa bis yang berseliweran di kota saya itu pula. Klaim sefihak saya ini mungkin terdengar muskil. Atau cerminan sikap arogan.

Tetapi, lihatlah beberapa bis mini (foto di atas) yang berseliweran di Wonogiri. Wajah, nama Beethoven beserta judul karya agungnya yang disukai Gus Dur itu, menghiasi dinding bis angkutan rakyat kota gaplek yang warganya rata-rata menggemari musik campur sari ini.
Namun terus terang, saya belum pernah menaiki bis-bis Beethoven tersebut. Jadi saya juga belum tahu apakah selama perjalanan dengan bis ini kita akan disuguhi musik dengan lirik, ”come sing a song of joy and freedom tell story ; sing sing a song of joy for mankind in his glory “ dari nomor “Song of Joy” tersebut. Atau justru suguhan musik campur sari ?
Blues dan obat bius. Selain nomor Beethoven di atas, seingat saya Gus Dur juga menyukai lagu “Me and Bobby McGee” dari penyanyi blues perempuan asal AS, Janis Joplin (1943-1970). Penyanyi ini telah diprofilkan oleh Gillian G. Gaar dalam bukunya, She's a Rebel: The History of Women in Rock & Roll (1992).
Janis Joplin mati muda karena heroin. Penyanyi cewek binal dengan gelar “sexually aggressive rock icon yang pada tahun 70-an saya nikmati foto-fotonya di majalah Aktuil, kebetulan pernah juga berurusan dengan presiden. Bukan dengan Gus Dur, tetapi dengan Dwight D. Eisenhower (1890–1969), presiden ke-34 Amerika Serikat.
Sebagaimana dilansir New Musical Express (12/4/1969), Joplin meluapkan kejengkelannya : “Empat belas kali terkena serangan jantung dan dia meninggal di minggu saya. Di Newsweek saya !” Pasal kejengkelannya itu gara-gara Eisenhower meninggal membuat foto dirinya gagal dipajang di sampul depan majalah Newsweek pekan itu !
Merujuk gambaran tentang Janis Joplin itu, bagi kalangan tradisionalis akan terasa nyleneh sekali saat mendapati seorang kiai NU, yang Islamnya cekek itu, tetapi menyukai lagu blues dari penyanyi yang mati muda akibat obat bius.
Itulah keunikan Gus Dur. Sebagai seorang pluralis, pejuang demokrasi, yang dirinya menghargai harkat kebebasan manusia, mungkin ia justru terinspirasi akan pesan dari lirik ”freedom's just another word ; for nothin' left to lose ; nothin', it ain't nothin' ; honey, if it ain't free” dari lagunya Janis Joplin tersebut.
Itu dugaan dangkal saya. Sekaligus merupakan pertanyaan pada diri saya yang belum tuntas terjawab. Bahkan sampai saat Gus Dur wafat.
“Bung Wimar,
Saya baru saja menulis sosok Gus Dur sebagai humoris yang pantas diteladani oleh para komediwan di Indonesia, karena menu "self-deprecating"-nya bersifat universal. Artikel itu berjudul "Dosa-Dosa Komedi Kita" di blog saya, Komedikus Erektus ! Saya ingin tanya : mengapa Gus Dur suka sama lagunya Janis Joplin, Me and Bobby McGee ? Makasih.”
Tiga tahun lalu, pada tanggal 4 Oktober 2006 (#21) saya telah menulis pertanyaan di atas pada blognya Wimar Witoelar. Setahu saya, Bang Wimar juga menggemari lagunya Janis Joplin tersebut. Dirinya pernah pula menjadi juru bicara saat Gus Dur menjadi presiden RI. Tetapi pertanyaan saya itu tidak memperoleh jawaban darinya.
Tak apa-apa. Itu tak begitu penting.
A Nation in Waiting, Again ? Karena banyak pertanyaan yang jauh lebih besar, lebih penting, adalah bagaimana Indonesia sepeninggal Gus Dur. Kaum minoritas, kaum yang selama ini kadang disingkirkan oleh negara, merasa seperti ayam kehilangan induk dengan wafatnya Gus Dur.
Juga tentang perjalanan demokratisasi di negeri ini. Di jaman Orde Baru, militer yang saat itu menjadi kepanjangan tangan tiran Soeharto memiliki ketakutan baru terhadap apa yang disebut oleh Adam Schwartz dalam bukunya A Nation in Waiting : Indonesia in the 1990s (1994) sebagai the extreme centrist, yaitu golongan yang mendorong demokratisasi dan penghargaan yang lebih terhadap hak asasi manusia.
Dalam buku yang di masa Orde Baru dilarang beredar dan dihadiahkan oleh warga Wonogiri di Jakarta, Mas Bambang Setiawan kepada saya tahun 2006 itu, Gus Dur tentu termasuk sebagai aktor pendorong dan motor vital dari gerakan ekstrim tengah itu. Soeharto pun tumbang di tahun 1998.
Tetapi di era reformasi yang sudah berjalan mendekati 12 tahun ini, perjuangan kaum ekstrim tengah itu memang boleh dibilang belum selesai. Tetapi daya gedornya, seiring meluasnya penggunaan media-media sosial di Internet, membuat rejim penguasa yang sebagian ditengarai berkomplot dengan konglomerat hitam untuk memperkaya diri sendiri, kini nampak hanya mampu bersikap defensif.
Termasuk menjulurkan tangan-tangan silumannya untuk menghambat rakyat memperoleh cerita tentang suara-suara kebebasan dan suara-suara kebenaran.
Upaya yang sia-sia.
Selamat jalan, Gus Dur. Suatu ketika rakyat Indonesia, termasuk penumpang bis-bis Beethoven di Wonogiri, akan menyanyi dengan suara agung sekaligus meresapi makna lagu “Song of Joy”-nya Beethoven ini :
Come sing a song of joy and freedom tell story
Sing sing a song of joy for mankind in his glory
Once mighty voice that will bring a sound
that will ring forever more
Then sing a song of joy for love
and understanding.
Wonogiri, 3-4 Januari 2010
ee

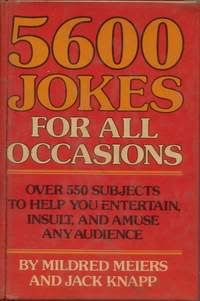
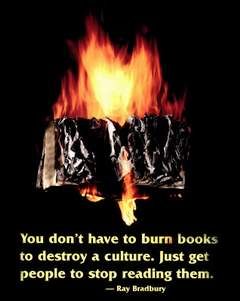




No comments:
Post a Comment