Oleh : Bambang Haryanto
Esai Epistoholica No. 106/Oktober 2010
Email : epistopress (at) gmail.com
Home : Epistoholik Indonesia
 Kinokuniya.
Kinokuniya.Mencari-cari buku di sana saya merasa seperti sedang berlatih karate di dalamnya.
Biang keroknya adalah fasilitas antarmuka dari anjungan elektronik yang disediakan toko buku itu. Dengan alat itu konsumen dibantu untuk menemukan buku-buku yang mereka cari di toko buku bersangkutan.
Layanan serupa bisa kita temui di pelbagai toko buku terkenal di Indonesia, berupa komputer, sementara di Kinokuniya itu wujudnya seperti kios ATM.
Ini bukan toko buku Kinokuniya yang berada di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta. Ini toko buku jaringan yang sama tetapi luasnya hampir sebesar lapangan sepakbola. Hamparan belukar buku yang menggairahkan itu membuat saya harus mengandalkan anjungan tadi untuk menemukan buku yang saya incar. Buku tentang manajemen ilmu pengetahuan.
Muncul masalah. Keypad-nya kurang begitu ramah. Ketika telunjuk menekan terlalu lemah, huruf tidak muncul. Tetapi ketika tekanan ditingkatkan ekstra, huruf yang muncul menjadi dobel. Saya membayangkan sedang berlatih karate, melakukan exercise guna memperkuat daya tohok jari-jemari saya.
Jadi sungguh perjuangan tersendiri untuk bisa menuliskan lema yang kita cari. Baik nama pengarang, judul atau subjek buku. Sementara pengguna lain dari toko buku megah di bilangan Orchard Road, Singapura itu, sudah pula nampak mengantri.
Buku yang saya cari itu, tidak saya temukan. Saya berandai-andai, alangkah menariknya bila terminal itu bisa agak "bercanda" dengan saya. Misalnya, bila buku itu tidak ada, ia dapat menyarankan saya untuk mengunjungi toko buku terdekat yang masih menyediakannya. Bahkan melalui Internet, sambungan itu bisa bercakupan dunia pula.
Jadi antar toko buku itu data koleksinya tersambung secara elektronik, 24/7. Diperkaya pula sambungannya dengan penerbit buku dan pengarang buku bersangkutan. Bahkan terintegrasi dengan data para pembaca buku tersebut, genap dengan segala komentar yang mereka tuliskan. Mengambil jargon dari ranah ilmu perpustakaan, ijinkanlah saya menyebut gambaran itu sebagai panorama tentang katalog yang menari.
Diagram kambing. Mengilas balik ke tahun 1980, mata kuliah tentang katalog, dengan label katalogisasi dan klasifikasi, bukan mata kuliah yang saya sukai. Pengampunya adalah Ibu Lily K. Somadikarta, yang saat itu adalah juga ketua jurusan Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Cara mengajarnya yang tegas dan direct, membuat kami yang belum mengenal akrab beliau menjadi cepat-cepat ciut nyali. Apalagi ini mata kuliah yang menentukan, apakah di tahun pertama kami langsung drop out atau berlanjut. Kuis atau tes pertama untuk mata kuliah ini saya mendapatkan nilai nyaris mendekati ambang batas kegagalan : 62.
Saat kuis, saya memang tidak menyangka diagram tentang alur proses penyimpanan dan penemuan kembali bahan pustaka itu muncul di kertas ulangan. Rupanya saya telah meremehkan jantung alur kerja perpustakaan ini. Sebab ketika mencatatnya saya telah membingkai diagram tersebut dengan garis kontur berwujud binatang kambing.
Teman sekelas saya, Subagyo Ramelan, tertawa-tawa melihat "diagram kambing" buatan saya itu.Bahkan ia mengomentari, "itu cara mencatat yang jenius." Ia yang kini membuka gerai "Safir Andaru" dan bergerak dalam bisnis batu mulia di Ciledug, Tangerang, ketika menjadi book officer di Asia Foundation pernah membantu saya memperoleh hibah puluhan buku-buku bermutu terbitan manca negara. Terima kasih, Bag.
Saya bayangkan, ke dalam mulut kambing itu masuk satu judul buku. Buku itu dikunyah, untuk diekstraksi. Wujud fisiknya disimpan di rak tertentu. Kalau jumlahnya puluhan atau ratusan, mungkin ingatan kita masih kuat mengingat sampul atau tempatnya untuk bisa ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Tetapi ingatan manusia ada batasnya. Bila jumlah buku itu sudah mencapai ribuan, masalah muncul. Menyimpan sih gampang, tetapi saat untuk menemukan kembali, secara cepat dan akurat ?
Solusinya, data buku itu harus dicatat. Secara sistematis. Ada ilmunya. Dalam buku besar, ia dicatat berdasarkan nomor urut, tanggal pembelian/hadiah, dan sumber buku tersebut. Ini untuk administrasi internal. Sedang untuk layanan bagi pemakai perpustakaan, isi buku dianalisis dulu, diklasifikasikan menurut subjek atau perihal, dengan merujuk panduan yang baku, seperti tabel DDC, Dewey Decimal Classification dan sarana bantu lainnya.
Kemudian tergabung di dalamnya pernak-pernik data buku lainnya, yang disajikan secara sistematis dalam bentuk kartu-kartu katalog. Pengunjung dapat mengakses koleksi perpustakaan melalui bantuan katalog tersebut berdasarkan nama abjad pengarang, judul buku, sampai subjek buku.
Pemahaman publik terhadap katalog sebagai sarana temu kembali bahan pustaka di perpustakaan, bukan hal yang otomatis. Bahkan juga di kalangan intelektual. Di kolom surat pembaca majalah Tempo (16/1/1982), saya pernah mengomentari isi acara "Dunia Pustaka" di TVRI (29/11/1981). Saat itu hadir bintang tamu seperti Harsja W. Bachtiar, Tuti Indra Malaon dan Toeti Adhitama.
Protes saya adalah : mahasiswa dan dosen harus dilatih agar mampu memahami fungsi katalog dan mahir memanfaatkannya dalam menemukan informasi yang relevan. Keterampilan serupa sekarang ini yang juga harus dilatih pada mereka, adalah pemanfaatan mesin pencari Google di Internet. Semua orang bisa menggunakan, tetapi tetap ada perbedaan signifikan antara mereka yang tidak terlatih vs mereka yang berpengetahuan tentangnya !
Konsumen adalah matahari. Itulah teori dasar dan praksis pengelolaan bahan pustaka yang jadul, yang saya pelajari di dekade awal 1980-an. Kini katalog-katalog kertas itu semakin banyak digantikan dengan sinyal-sinyal elektronik. Otomasi. Komputerisasi.
Tetapi sebagai seorang renegade, yang terciprat DNA ilmu perpustakaan tetapi tidak pernah bekerja sebagai pustakawan sejak 1985, saya tidak tahu seberapa jauh, juga seberapa sukses otomasi itu telah berjalan di pelbagai perpustakaan dunia dan Indonesia.
Ketika di tahun 1996, awal kali menggunakan Internet di stan pameran USI-IBM di Wisma Bapindo dengan memposkan email di situs Olimpiade Atlanta untuk Susi Susanti, Alan Budikusuma dan kawan-kawan (juga adik saya) di Atlanta, lalu mengenal katalog raksasa di Internet berupa direktori Yahoo ! saat itu, dan kini mesin pencari Google, saya merasa ilmu perpustakaan (pola jaman saya) dan juga institusi perpustakaan sedang menuju senjakala. Minimal, relevansinya terancam semakin terus menyurut.
Di harian Suara Karya saat itu saya pernah menulis surat pembaca, berpendapat bahwa dulu lanskapnya perpustakaan sebagai matahari dan para pemakai merupakan planet-planet yang mengelilinginya. Kini di era Internet, posisinya terbalik. Pemakai informasi adalah matahari dan pelbagai jasa layanan informasi yang ada saat ini, termasuk perpustakaan, merupakan planet-planet yang mengelilinginya.
Dalam dunia korporasi, meminjam pendapat pustakawan yang kini menjadi konsultan bisnis Internet tingkat dunia, Mary J. Cronin dalam bukunya The Internet Strategy Handbok : Lessons from the New Frontier of Business (Harvard Business School Press, 1996), pelanggan adalah matahari yang dikelilingi pelbagai unsur-unsur fungsi inti perusahaan. Tidak hanya terkait dengan bagian pelayanan pelanggan dan komunikasi korporat, tetapi juga merengkuh kepada bagian pengembangan produk, riset, sistem, personalia, manajemen informasi,penjualan, pemasaran sampai distribusi produk.
"Interaksi secara konstan dengan basis konsumen, memperoleh umpan balik untuk setiap fase pengembangan produk, dan kemampuan mengorkestrasi beragam bagian untuk hadir sebagai customer support dan tim umpan balik, menunjukkan bahwa pelanggan hadir sebagai komponen sentral semua aplikasi berbasis Internet," demikian tegas professor Carroll School of Management dari Boston College tersebut.
Revolusi media sosial. Para pustakawan dan pegiat otomasi perpustakaan di Indonesia kiranya pantas mendengar nasehat Ibu Mary yang anggun dan karismatis itu. Konsumen adalah matahari. Sudahkah pola pikir itu terintegrasi dalam layanan perpustakaan, yang sudah menggunakan layanan secara otomasi ?
Untuk mencoba mencari tahu hal itu, hari Sabtu (23/10/2010), sebagai hari wajib kunjung ke Perpustakaan Umum Wonogiri, saya bertanya kepada petugasnya, mBak Wening. Apa nama peranti lunak untuk organisasi koleksi perpustakaannya. Dia jawab : Limas. Lalu saya tanya, apakah ada fitur yang memberi peluang bagi peminjam untuk menulis sesuatu tentang buku (yang dibacanya) itu ? Ia jawab lagi : tidak ada.
Sebelum berangkat, saya sempat kirim SMS ke Ahmad Subhan, pustakawan dan aktivis literasi di Yogya. Semula kami hanya bisa saling kenal melalui Internet, lalu bisa ketemuan secara serendipity pada acara Jagongan Media Rakyat (JMR) 2010, 24 Juli 2010 di Jogja National Museum, Yogyakarta. Beberapa saat sebelumnya ia baru ngeh kalau kita sama-sama memiliki DNA ilmu perpustakaan.
Isi SMS saya : Pagi Subhan. Di "Senayan" ssudah data buku apa ada kolom komentar user ttgnya, spt @ Amazon.com ? Sdh bc blog "Expired but still Wired" di blogroll jipfsui80-ku ? Tks. (Sabtu, 23 Oktober 2010 : 06.51.23).
Ia membalas : Pagi jg pak. Senayan blm ada fitur komen. Tp itu ide bagus, prlu diusulkn ke m'hendro. Sy prnah bc blog itu, isinya bgs, khususnya tlsn ttg fenomena pola membaca "F" (Sabtu, 23 Oktober 2010 : 07.19.26).
Hendro yang ia maksud adalah Hendro Wicaksono, Head Developer Senayan Library Automation. Inilah "Senayan" yang saya maksud di SMS di atas tadi. Senayan adalah perangkat lunak perpustakaan milik Departeman Pendidikan Nasional (Depdiknas). Bahkan karya cipta anak negeri ini telah memenangkan kategori Open Source System dalam Indonesia ICT Awards 2009 yang baru lalu.
Hendro yang alumnus JIP-FSUI 1992 ini, secara ajaib dan mungkin sudah tergaris di kosmis, tiba-tiba menghuni satu kamar bersama diri saya di wisma Jogja National Museum, 23-25 Juli 2010. Dia dari Jakarta dan saya dari Wonogiri, saat itu jualan Epistoholik Indonesia, kami sama-sama diundang menjadi nara sumber pada helat pertemuan aktivis media akar rumput di Jagongan Media Rakyat (JMR) 2010 Yogyakarta.
Sesudah sowang-sowang saya merasa kurang beruntung. Presentasi Hendro Wicaksono waktunya bersamaan dengan penampilan teman yang saya kenal melalui Internet, pegiat budaya Internet Sehat, Donny Budi Utoyo, dari ICT Watch. Menempati pendopo, yang sehari sebelumnya tempat saya menjual komunitas EI saya, pengunjung sudah disihir dengan sajian video dari YouTube yang berkisah mengenai "Social Media Revolution"" yang menggelegak. Di mana kita segera dihentak oleh lagu hip-hop Fat Boy Slim yang tak henti-hentinya berteriak : "Right here, right now ; right here, right now ; right here, right now !".
Revolusi media sosial memang telah terjadi sekarang ini. Merujuk hal itu saya memutuskan untuk mengikuti sesi presentasi dari Donny B.U. ini, dan tentang Senayan-nya Hendro, terpaksa saya tinggalkan. Dalam konteks kepentingan komunitas EI saya, inspirasi tentang media sosial saya rasa lebih sedikit relevan dibanding bercerita tentang perpustakaan. Utamanya, hemat saya, karena yang pertama lebih banyak menyimpan cerita sebagai bahan eksekusi pendekatan yang inside out, yang berorientasi kepada khalayak, pembaca atau konsumen, dibanding wacana yang kedua saat itu.
Saya memang sempat menyelinap masuk ke ruangan Hendro tempat ia melakukan presentasi. Saat itu berlangsung sesi tanya jawab. Nampak moderator, Yossy Suparyo, rada kesulitan menemukan audiens yang mau tampil untuk berkomentar. Jumlah audiensnya lebih banyak daripada yang hadir di pendopo tadi.
Membanggakan juga melihat generasi muda pustakawan yang begitu antusias untuk menguasai perangkat lunak otomasi ini. Bahkan di Yogyakarta ini, komunitas untuk belajar bersama sudah terbentuk, dan boleh dibilang Hendro sudah menaiki tahta sebagai "raja" di antara mereka dengan bersenjatakan keris sakti berwujud peranti lunak Senayan itu pula.
Sayang, ketidakberuntungan saya masih berlanjut. Unduhan peranti lunak Senayan dari Hendro tersebut kini masih "terkunci" di flashdisk saya yang bermasalah berat. Tidak bisa diakses. Padahal belum pernah saya baca-baca isinya, minimal sejarah proses perjalanan Senayan sampai kini. Mungkin itu penyebab :-( sms saya ke Hendro, belum ia jawab. Saya bertanya :
Siang, Hend. Minta info : 1. Apa perpus2 user Senayan saling terkonek scr online, 24/7 ? 2.Ada fitur utk interaksi peminjam2 buku dg pustakawannya scr online pula ? Tks. (Sabtu, 23 Oktober 2010 : 13.42.28).
Market place vs market space. Di perpustakaan Wonogiri, dengan akses Internet yang selama proses loading bisa saya gunakan waktunya untuk baca-baca koran, saya juga mengirim pertanyaan di akun Facebooknya Hendro Wicaksono.
"Apakah Senayan menomor satukan functionality dari bahan pustaka, pinjam-kembali semata, tetapi belum mengeksploitasi sisi-sisi interaksi antara user/peminjam dengan bahan pustakanya, and beyond ?"
Senayan adalah katalog elektronik. Kalau katalog-katalog kertas yang berukuran 3 x 5 inci itu sangat terbatas untuk diutak-atik, maka katalog elektronik menurut hemat saya membuka peluang maha lebar untuk dieksploitasi. Tidak hanya terbatas sebagai sarana temu kembali bahan-bahan pustaka belaka.
Meminjam pendapat Jeffrey F. Rayport, yang dulu adalah dosen di Harvard itu, kartu-kartu katalog kertas dan koleksi buku itu bisa dijuluki sebagai marketplace, wahana fisik. Sementara katalog elektronik adalah marketspace, suatu lingkungan maya tempat berlangsungnya transaksi dan interaksi secara elektronik. Lingkungan ini ibarat lempung, tanah liat komunikasi yang membuka peluang untuk dieksplorasi sejauh batas-batas imajinasi.
Saya bertanya-tanya : apakah eksekusi katalog elektronik Senayan itu masih memakai kerangka pikir marketplace ? Atau kah sudah merambah ke kerangka pikir yang revolusioner dan benar, yaitu sebagai marketspace ? Bahkan sudah pula dirancang untuk ikut menggelincir sebagai pelaku dalam badai revolusi media sosial yang sedang terjadi ?
Gus Doerr menjawab. Gara-gara mencari info terbaru tentang Pak Jeffrey F. Rayport tadi (saya mengagumi saat membaca artikelnya "Managing in the Marketspace" di majalah Harvard Business Review, Nov/Dec 1994) dengan memanfaatkan Google, bukan melalui sarana bantu katalog kertas di perpustakaan Wonogiri (yang tidak ada) atau katalog online yang belum dioperasikan untuk pengunjung ("menunggu lengkap," kata mBak Wening), saya ketemu artikel menarik.
Terdapat di situs majalah Fast Company yang bergengsi. Versi cetaknya selalu bikin ngiler saat terpajang di toko buku QB World Books, Jl. Sunda, Jakarta Pusat. Artikel dari majalah itu bercerita tentang Gus Doerr.
Nama lengkapnya John Doerr, dari perusahaan Kleiner Perkins Caulfield & Byers yang teramat amat sohor di bidang dunia teknologi informasi. Perusahaan venture capital raksasa ini telah membidani lahirnya perusahaan-perusahaan Internet kelas dunia. Misalnya, Google, Amazon, Sun Microsystems, juga Electronic Arts, Symantec, sampai Netscape.
Gus Doerr bilang : terjunlah kini ke media sosial atau Anda akan keteteran. Menurutnya, media-media sosial seperti blog, Facebook dan Twitter dan ribuan jenis lainnya, merupakan gelombang ketiga dari disrupsi Internet. Gelombang pertama adalah terciptanya Internet itu sendiri ("terima kasih banyak, Pak Tim Berners-Lee").
Gelombang kedua adalah penemuan peramban, browser, yang membuat semua orang mampu menjelajahi web. Dan sekarang menurut Gus Doerr, Internet sedang berubah lagi. Dari "Internet lama yang berbasis dokumen dan situs menuju sosok baru yang meliput semuanya tentang manusia, tempat dan hubungan."
Terima kasih Gus Doerr, untuk wawasan Anda.
Tohokan keras. Terakhir : dalam konstelasi perubahan besar yang sedang terjadi ini, di manakah sosok dan krida pustakawan Indonesia berada ? Barangkali secara guyon kita bisa bercermin dengan menghitung-hitung karakter dari istilah "pustakawan" itu sendiri.
Kata "pustakawan" terdiri atas 10 huruf. Kata "pustaka," terdiri dari tujuh huruf, 70 persen. Merujuk benda. Kata atau imbuhan "wan," terdiri tiga huruf, 30 persen. Merujuk manusia. Jadi pustakawan Indonesia proporsinya jauh lebih suka dan lebih berfokus untuk mengurus benda-benda, tetapi abai untuk melayani manusia ? Lihatlah pula pesan dalam logo organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia. Barangkali Anda juga telah memperoleh jawab yang sama dari sana.
Bila memang semua itu yang terjadi, tak ayal bila profesi ini akan segera menjadi tidak relevan lagi di tengah badai perubahan.
Kinokuniya.
Dengan meminjam kenangan saat menotok tombol-tombol keypad anjungan informasi di toko buku itu, apakah kira-kira gugatan seorang renegade ini merupakan tohokan keras ? Atau hanya gelitikan yang tidak dianggap penting bagi masa depan dunia perpustakaan dan kepustakawanan kontemporer di Indonesia ?
Wonogiri, 24 Oktober 2010
ee

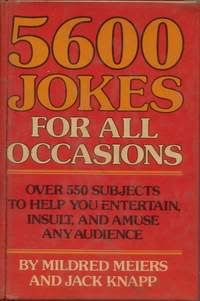
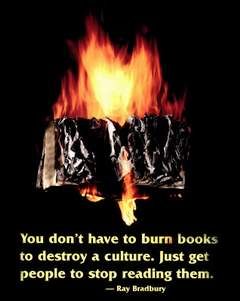




No comments:
Post a Comment