Ketika atlet-atlet kita diperkirakan gagal memperoleh emas di ajang akbar tersebut, sempat muncul khayalan: apabila Ranomi itu atlet yang digembleng di Indonesia, apakah dirinya akan memperoleh emas pula?
Kita bisa menengok apa yang terjadi di Olimpiade Los Angeles 1984. Saat itu, mengapa Brasil hanya mampu meraih satu medali emas dari Ricardo Prado, sementara Amerika Serikat berpesta memborong 30 medali emas dari ajang yang sama, yaitu kolam renang? Padahal keduanya sama-sama negara besar di benua Amerika.
Untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini, kita dapat menyimak tesis profesor psikologi dari California State Universty di Fresno, Robert Levine, tentang apa yang disebut sebagai waktu sosial, denyut jantung masyarakat dalam memaknai waktu.
Benturan budaya. Secara matematis manusia hidup dalam hitungan waktu yang sama, 24 jam sehari, tetapi tidak semua budaya di dunia memaknainya secara sama. Levine yang seorang Amerika, merasakan benturan budaya akibat beda pemaknaan waktu ketika mengajar di sebuah universitas di Brasil. Juga ketika melakukan kajian lanjutannya ke berbagai kawasan di dunia, termasuk di Jakarta dan Solo.
Hari pertama Levine di Brasil dijadwalkan mengajar pukul 10.00 waktu setempat. Ia datang pukul 09.05, lalu berkeliling untuk mengenal kampus itu. Ia pikir dirinya baru berkeliling sekitar setengah jam tetapi langsung panik ketika melihat jam di salah satu gedung kampus menunjuk waktu pukul 10.20.
Ia bergegas masuk ruang kuliah, ternyata tak ada satu pun mahasiswa. Ia tanya jam pada mahasiswa yang lewat, dijawab pukul 09.55. Lainnya menjawab, tepat pukul 09.43. Sebuah jam di gedung itu menunjuk waktu pukul 09.15. Ia berpendapat, jam-jam penunjuk waktu yang ada tidak akurat tetapi tak ada orang yang hirau.
Ketika kuliah dimulai, banyak mahasiswa yang telat masuk ruang. Beberapa baru masuk pukul 10.30 dan mendekati pukul 11.00. Semuanya tampak merasa tidak bersalah, tersenyum dan mengucap ”halo”, dan mahasiswa lainnya pun tampak tak terganggu.
Dalam risetnya, mahasiswa Brasil menyatakan seseorang datang terlambat bila ia muncul rata-rata 33 menit melewati janji, sementara mahasiswa Amerika Serikat menyebut 19 menit. Setelah beberapa lama tinggal di Brasil, ia baru terbuka matanya bahwa budaya yang mempengaruhi pemaknaan waktu sosial itu.
Terungkap pendapat di kalangan mahasiswa Brasil bahwa seseorang yang secara konsisten terlambat itu lebih sukses dibanding mereka yang konsisten datang lebih awal. Mereka menyetujui pendapat umum bahwa seseorang yang berstatus tinggi harus datang terlambat. Ketidaktepatan waktu merupakan simbol sukses. Melihat fenomena Brasil ini, kita bangsa Indonesia seperti memperoleh cermin.
Meriset wong Solo. Lebih menarik ceritanya ketika Levine bersama kolega kampusnya, Kathy Bartlett, melakukan riset untuk memperkaya pemahaman tentang konsep waktu sosial berbagai bangsa. Mereka melakukan pengukuran waktu terhadap irama hidup di kota besar dan kota menengah di berbagai belahan dunia.
Di antaranya di Jepang (Tokyo dan Sendai), Taiwan (Taipei dan Tainan), Indonesia (Jakarta dan Solo), Italia (Roma dan Florence) dan Amerika Serikat (New York dan Rochester). Riset itu mengkaji tiga indikasi dasar: akurasi jam pada kantor bank, kecepatan pejalan kaki dan kecepatan pegawai kantor pos melayani pembelian perangko.
Akurasi waktu terbaik diraih Jepang. Alat penunjuk waktu di 15 kantor bank yang dicek dengan waktu kantor telepon setempat hanya berselisih kurang atau lebih setengah menit. Di Indonesia, yang menempati peringkat paling buncit dari keenam negara itu, selisih beda waktunya lebih dari tiga menit.
Kecepatan seseorang sendirian berjalan kaki menempuh jarak 100 ft yang terbaik adalah orang Jepang. Rata-rata waktu tempuhnya hanya 20,7 detik. Orang Inggris menempuhnya 21,6 detik, orang Amerika 22,5 detik dan orang Indonesia berstatus paling lambat dengan waktu tempuh 27,2 detik.
Hasil riset Robert Levine yang dituangkan dalam majalah Psychology Today (3/1985) memberikan ilustrasi ketika ia mengukur efisiensi petugas pos melayani pembelian perangko. Di Solo, saat itu hari Jumat, ia datang siang. Tentu saja kantor pos sudah tutup lebih awal, untuk Salat Jumat.

Harian Solopos, Rabu, 8 Agustus 2012 : Halaman 4.
Pada hari lain ketika ia antre di kantor pos. Pegawai pos yang menjual perangko malah asyik mengajaknya mengobrol membicarakan kerabatnya yang tinggal di Amerika. Lima orang yang antre di belakang Levine tampak sabar. Mereka tidak mengeluh dan bahkan ikut nimbrung atas obrolan mereka.
Walaupun demikian, efisiensi waktu pegawai pos Indonesia berada di peringkat ke-5 sebab yang paling buncit diduduki pegawai pos Italia. Waktu layanan di Jepang 25 detik dan Italia memakan waktu 47 detik!
Korupsi waktu. Gambaran mengenai profil waktu sosial bangsa Indonesia dalam riset Levine di atas sedikit banyak mampu memberikan gambaran mengenai posisi bangsa dan negara ini dalam berpacu dengan bangsa lain di kancah internasional. Di kancah olahraga misalnya, seperti halnya Brasil, atlet perenang atau lari dari Indonesia belum pernah tercatat punya prestasi puncak di kancah seakbar olimpiade.
Sementara dalam kehidupan sosial, guru besar emeritus Intitut Pertanian Bogor (IPB), Sjamsoe’oed Sadjad (Kompas, 17 Juli 2004), menandai bahwa budaya korupsi waktu kronis melanda para pegawai negeri sipil kita.
Ia berhitung bila 3,5 juta PNS melakukan korupsi waktu hanya satu jam setiap hari maka 3,5 juta jam sehari rakyat kehilangan kesempatan untuk dilayani. Hitungannya, untuk pegawai negeri bergaji Rp8,4 juta/tahun maka akibat korupsi waktu satu jam itu negara dirugikan Rp16 miliar tiap hari.
Belum lagi korupsi satu jam pada hari. Juga belum lagi kalau gajinya lebih besar dari Rp700.000/bulan. Bayangkan bila gajinya Rp150 juta seperti gaji direktur utama Pertamina. Hitung saja, bila datang ke kantor pukul 10.00.
Seperti di Brasil, di Indonesia juga berlaku tradisi bahwa semakin tinggi pangkatnya maka pejabat Indonesia boleh dan berhak selalu datang telat. Para dosen di perguruan tinggi datang ke kampus hanya kalau memberi kuliah.
Anehnya, kata Prof Sadjad, rakyat tidak merasa dirugikan. Rakyat tidak sadar uangnya ”digerogoti”. Apakah karena negeri ini gemah ripah loh jinawi sehingga kehilangan Rp16 miliar/hari masih bisa membuat kita terus tertawa-tawa?
Budaya mencatat. Kembali ke Ranomi Kromowidjojo. Merujuk realitas pahit di atas, rasanya sulit untuk menyabet emas di olimpiade apabila dirinya sebagai atlet Indonesia. Ada tambahan informasi: di dunia yang maju, tiap atlet renang dan keluarganya selalu punya catatan prestasi renangnya dari hari ke hari. Baik dalam latihan atau pun perlombaan. Catatan itu sebagai landasan untuk memperbaiki prestasi.
Pada diri kita?
Budaya mencatat serupa belum punya akar kuat dalam tradisi bangsa kita.
Begitulah, prestasi kita di Olimpiade London 2012 semakin menunjukkan betapa bangsa lain telah lari berpacu, kita terus-menerus merasa senang jatuh bangun, keserimpet budaya korupsi, termasuk juga korupsi waktu tanpa kita menyadari kerugiannya !
Wonogiri, 8 Agustus 2012


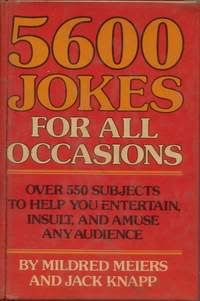
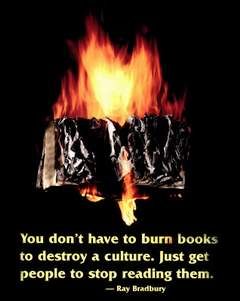




No comments:
Post a Comment